Cerdas. Tawakal. Akhlak Mulia. Santun. Berbudi Luhur. Slogan-slogan macam ini sangat biasa ditemukan di tembok-tembok sekolah. Apakah itu artinya? Itu semua menunjukkan nilai-nilai yang layak diperjuangkan dan dikejar oleh segenap warga sekolah. Namun, dalam implementasi di kelas, dalam kurikulum yang dikembangkan guru, dan dalam interaksi antar satu dengan yang lain, bagaimana slogan-slogan tersebut diwujudkan? Jawabnya: SULIT!
Hal ini sebenarnya bukan hal yang berlebihan mengingat tujuan pendidikan itu beragam, sesuai dengan dasar keyakinan yang membentuk kita. Bagi sejumlah orang, pendidikan diutamakan untuk meletakkan dasar-dasar keimanan. Bagi sekelompok lain, pendidikan lebih untuk mempersiapkan penguasaan keterampilan teknis. Bagi golongan tertentu, pendidikan lebih ditargetkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Mana yang kita yakini?
Salah satu model yang sampai sekarang ini masih eksis adalah model rekonstruksi sosial. Secara historis, hancurnya sistem kapitalisme yang mendorong terjebaknya dunia dalam Depresi Besar 1929 membuat banyak ahli pendidikan jengah dan sekaligus mempersoalkan kebenaran dari sistem kapitalisme. Salah satunya Harrold Rugg. Dia membuat analisis kritis mengenai kebohongan ilmu sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah. Pada tahun 1939, dia menerbitkan serangkaian buku teks yang mengubah lanskap pendidikan di Amerika Serikat. Dia mengajarkan pentingnya para anak didik untuk tidak sekedar menerima “kebenaran” yang dicekokkan oleh otoritas, namun justru mencari sumber belajar untuk mempersoalkan “kebenaran” yang coba ditanamkan oleh otoritas. Harrold Rugg menolak agenda pemerintah untuk membentuk para siswa menjadi sosok-sosok pasif tanpa mempersoalkan kebenaran yang dipaksakan. Dua tahun pertama Harrold Rugg menerbitkan bukunya, dia tercatat sebagai pemegang rekor sebagaibest-selling author, karena bukunya terjual lebih dari 6 juta eksemplar. Uniknya, begitu Jepang membombardir Pear Harbor 7 Desember 1941, Harrold Rugg yang populer karena sikap anti pemerintahnya dicampakkan dan dinilai tidak punya patriotisme!
Namun demikian, teori rekonstruksi sosial tidak mati. Ira Shor (1992) mengajarkan pendekatan pedagogi demokratis-kritis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, dia mengajak para siswanya untuk menuliskan esay pribadi dengan tema pengembangan diri masing-masing siswa. Berikutnya, dia mengajak anak didiknya untuk memahami topic “bagaimana upaya pengembangan diri kita masing-masing ditentukan oleh ketersediaan sumber daya (ekonomis).” Dia menghadirkan serangkaian bacaan tentang contoh-contoh mengenai bagaimana banyak perusahaan lari dari kota untuk mengembangkan usahanya di daerah-daerah yang lebih murah tenaga kerjanya. Sementara itu, ada juga bacaan-bacaan yang menggambarkan keputusan pemerintah untuk mempertahankan agar perusahaan-perusahaan ini tetap tinggal di kota. Ira Shor kemudian mengajak para siswanya untuk menimbang dan mendiskusikan bagaimana kondisi ekonomi macam ini memunculkan kebijakan ekonomi tertentu, dan kemudian dampak-dampak macam apa yang akan mempengaruhi pajak, pelayanan kota, dan biaya pendidikan. Mereka akhirnya bisa mengaitkan bahwa esay pribadi tentang pengembangan diri sangat erat kaitannya dengan konteks sosial ekonomi di tempat mereka tinggal.
Model rekonstruksi sosial ini memang berorientasi pada terciptanya sikap kritis. Siswa diharapkan tidak hanya sekedar menerima apa yang diusung oleh guru. Dan guru pun harus siap dengan serangkaian strategi untuk mengajak anak berpikir kritis. Ira Shor menampilkan serangkaian bacaan yang menantang para siswanya untuk berpikir tentang keadilan gender. Di salah satu bacaan, dikisahkan para wanita Irlandia yang mengerjakan pekerjaan kasar, yang bekerja dalam kondisi yang jauh dari ideal dan dibawahi oleh dominasi laki-laki. Dia mengajukan beragam pertanyaan untuk menggiring kesadaran kritis akan ketidaksamaan posisi pria dan wanita dalam lingkup kerja.
Dapat diambil kesimpulan bahwa model rekonstruksi sosial ini ditandai dengan lima langkah.
1. Mengidentifikasi suatu isu yang paling problematik,
2. Mempelajari realitas dari kehidupan para peserta didik, termasuk kesulitan dan sumber-sumber persoalannya,
3. Mengaitkan beragam persoalan tersebut dengan lembaga dan struktur dalam masyarakat yang lebih luas,
4. Mengaitkan norma sosial dengan norma-norma dan cita-cita ideal yang mereka miliki dalam kaitannya dengan kehidupan di masyarakat mereka, dan
5. Mengambil peran dan tanggung jawab untuk membuat situasi lebih sesuai dengan harapan.



 03.57
03.57
 Dara Zarbiah
Dara Zarbiah

 Posted in:
Posted in: 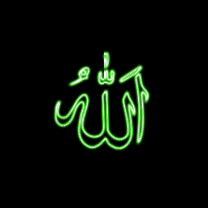

0 komentar:
Posting Komentar